Hampir sepekan di Jakarta, tempat-tempat yang saya
kunjungi berada tak jauh dari stasiun kereta api sehingga saya selalu naik KRL/Commuter Line yang bisa dibilang
menyenangkan, dibandingkan pengalaman saya dengan moda transportasi ini ketika
saya tinggal di Jakarta. Pernah pada tahun 2010 saya beserta istri dan dua anak
saya yang masih kecil-kecil naik KRL untuk menghadiri sebuah resepsi pernikahan
di Masjid Sunda Kelapa. Karena kereta sangat penuh dan saya tidak mendapat
pegangan saat menggendong anak saya dan nyaris sulit bernapas karena sesaknya
penumpang, kami akhirnya memilih turun di Cawang bukannya Cikini. Dibandingkan
kondisi lima tahun silam, perkembangan KRL boleh dibilang luar biasa. Belum lagi
kalau ingat pemandangan tiap sore di lintasan kereta api Tanjung Barat di mana orang
menyemut di atap KRL.
 |
| Di Stasiun Tanjung Barat, September 2010 |
Dengan Tiket Harian Berjaminan berbentuk kartu yang saya
beli di Stasiun Pasar Senen seharga Rp12.000 (Rp10.000 untuk kartu dan Rp2.000 untuk
ongkos perjalanan Pasar Senen – Palmerah) saya cukup membayar masing-masing Rp2.000
untuk pergi ke Stasiun Pasar Minggu, Stasiun Cawang, Rp4.000 untuk mencapai
Stasiun Bogor, dan RP5.000 untuk perjalanan dari Stasiun Bogor ke Stasiun Manggarai. Murah saja. Cara memperoleh tiket dengan membeli di loket memang
kalah modern dibanding cara mendapatkan tiket MRT di Singapura, tetapi sebagai generasi
karcis domino yang pernah naik keretaapi uap saya lebih menyukai cara pembelian yang melibatkan penjual, bukan
mesin. Kartu jaminan KRL berlaku selama 7 hari. Dan tak sampai tujuh hari saya
sudah pulang ke Yogyakarta dengan kereta api Bogowonto.
 |
| Karcis KRL Bogor - Jakarta |
 |
| Tiket Jaminan Rp10.000 |
Saya membeli tiket langsung pada hari keberangkatan di
Stasiun Senen. Tadinya saya ingin naik KA Progo yang harga tiketnya Rp75.000,
tetapi sudah habis. Jadilan saya beli tiket KA Bogowonto seharga Rp220.000 yang
berangkat pada pukul 21.45 pada tanggal 21 Januari 2016. Ada yang mengherankan
ketika saya keluar dari tempat pembelian tiket dan berjalan menuju peron
pemberangkatan: seseorang duduk dan berkata pelan, “Tiket. tiket”. Dengan sistem
serapi itu (yang mengharuskan pembeli menunjukkan kartu identitas dan di tiket
dicantumkan nama serta nomor kartu identitas penumpang) apa yang bisa dilakukan
para calo? Entahlah.
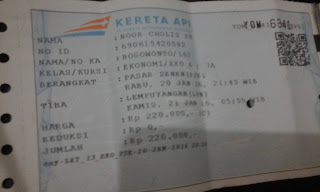 |
| Tiket KA Bogowonto Pasar Senen - Lempuyangan |
Kereta berangkat tepat waktu. Saya duduk sendiri. Di
depan saya duduk seorang bapak dengan mata kiri diperban ditemani anaknya.
Bapak asal Klaten yang mengadu nasib di Jakarta itu hendak menjalani operasi
mata di RS Mata Dr. Yap karena matanya terkena serpihan kayu saat bekerja. Saya
bertanya bagaimana bisa kemasukan serpihan kayu, bukankah untuk pekerjaan
berbahaya ada kewajiban mengenakan pengaman, misalnya kacamata. Bapak itu
membenarkan seraya berkata, “Tapi ya bagaimana lagi, karena sudah biasa jadi
merasa tidak perlu memakai pengaman.” Ini kecelakaan kerja kedua yang dia
alami, dia menunjukkan jari-jari tangan kanannya yang tak punya ruas kuku karena
terlindas peralatan mengolah kayu. Saya tak bisa berkomentar apa-apa dengan kebiasaan
orang kita menggampangkan aturan keselamatan. Dahulu, dalam perjalanan naik
kereta juga (Bangunkarta) saya pernah mengobrol dengan anak muda yang bekerja
membangun menara BTS yang menceritakan karena sudah biasa dia tak pakai alat
pengaman apa pun saat bekerja di ketinggian yang penuh risiko. Saya hanya bisa
bingung dalam hal ini.
Kereta api Bogowonto memasuki Stasiun Tugu tepat seperti yang
tertera dalam tiket, pukul 05:55. Setelah bersalaman dan mengucapkan harapan
semoga segala urusannya dimudahkan kepada bapak beranak rekan perjalanan saya
itu, saya turun dari gerbong dan menuju pintu keluar seperti biasa. Rupanya ada
perubahan, penumpang tidak boleh lagi keluar melewati gerbang depan stasiun.
Pintu keluar hanya ada satu, bukan di sisi selatan stasiun (yang kini hanya diperuntukkan
bagi lansia dan penyandang cacat)* melainkan di ujung barat selatan stasiun.
Ini sungguh menjengkelkan bagi saya yang berniat berjalan kaki hingga Tugu agar
nanti tak perlu memutar lewat Jembatan Kewek ketika dijemput istri saya. Di
pintu keluar sudah berderet-deret sopir taksi dan tukang ojek yang menawarkan
jasa sedemikian agresif hingga terkesan mengganggu. Saya tak pernah mau menggunakan
jasa mereka karena harga yang tidak masuk akal. Celakanya, angkutan umum yang lewat
dekat Tugu hanya Trans Jogja. Itu pun haltenya cukup jauh dari stasiun jika
dicapai dengan berjalan kaki. Entah kapan hal begini dibereskan. Mestinya bisa.
Stasiun-stasiun dan kereta api yang dahulu penuh pedagang asongan dan pengamen saja
bisa dibereskan. Sistem transportasi kereta api yang terpadu dengan baik seperti
di Kuala Lumpur, Bangkok, dan Singapura tampaknya masih jauh dari harapan.
* Bunyi
pengumuman di pintu keluar selatan adalah “Pintu keluar khusus lansia dan
difabel. Saya tak tahu apakah penyebutan difabel dimaksudkan untuk menghapus
kata penyandang cacat atau menghemat karakter. Hobi kita dengan eufimisme sering
tak masuk akal bagi saya.
No comments:
Post a Comment