Buku adalah jendela dunia. Mungkin karena ungkapan itu begitu kuat terpatri dalam benak, saya tidak terlalu berminat bepergian ke luar negeri (Makkah adalah perkecualian). Meski saya sepakat bahwa mengunjungi suatu tempat sangat berbeda rasanya dengan hanya membaca tentang tempat tersebut. Menulis kisah fiksi dengan latar sebuah kota di Belanda tetapi tak pernah menginjakkan kaki di Negeri Belanda tentulah lucu, kalau bukan berbuntut malu seperti yang pernah menimpa seorang penulis. Dan saya tidak bisa menulis fiksi. Membuat paspor pun dahulu karena ditugaskan ke luar negeri yang laporannya harus ditulis dalam bentuk non-fiksi.
Tulisan-tulisan di blog yang menceritakan betapa
penulisnya keranjingan melakukan lawatan ke berbagai negeri hingga kecanduan
itulah, antara lain, yang membuat saya ingin membuktikan banyak hal yang
ditulis orang. Dari semua yang saya baca, mulai dari yang bergaya penulis
tenar, sampai yang asal tulis hingga dua tiga kalimat saja sudah saya tutup,
blog milik seorang bapak sepuh dengan
nama blog ikutsangsurya saya rasa yang paling mengesankan. Keterangannya benar,
gaya penulisannya bersahaja, tidak menggurui lagi tidak berpretensi bijak,
tulisan-tulisannya tidak menyiratkan keinginan untuk mengabarkan bahwa
perjalanan membuatnya berlimpah pengalaman hidup. Penuturan apa adanya tentang
perjalanannya ke Siem Reap sangat
saya sukai. Hormat saya untuk beliau.
Soal Kota Ho Chi Minh, saya kagum dengan tulisan seorang perempuan muda (tampaknya alumna
sebuah universitas di London) yang menuliskan pandangannya tentang Saigon dalam bahasa
Inggris yang sempurna. Baginya, tak ada yang menarik dari Saigon karena
kemiripannya dengan Jakarta. Kata dia Saigon mungkin memikat bagi orang Barat,
tapi seperti pindah tempat saja bagi kita. Walaupun beredarnya di mana dan kapan tampaknya berpengaruh juga. Di pagi hari menunggu Dormitory Guesthouse buka, sebuah sepeda motor polisi meraungkan sirene mengawal sepeda motor berpenumpang tiga orang, pengendaranya berseragam polisi, memboncengkan dua orang, yang di tengah diborgol, yang paling belakang berpakaian preman. Muka ketakutan pesakitan itu sangat menjelaskan bagi saya bahwa Saigon sama sekali bukan Jakarta, apalagi sepeda motor bersirene maupun yang di belakangnya cuma sepeda motor bebek. Namun, secara garis besar saya sepakat
dengan pandangan mbak itu. Sayangnya tak banyak tulisan di internet soal perjalanan
yang bagus selain Pak Ikutsangsurya dan Mbak London itu.
Upaya “membuktikan” tulisan orang jugalah yang membuat
saya sengaja bermalam di Bandara Tan Son Nhat, kendati pesawat yang akan
menerbangkan saya ke Singapura baru
berangkat keesokan harinya pukul 08.55. Dikisahkan bahwa pengalaman tidur di
bandara Kota Ho Chi Minh itu begitu mendebarkan hingga si penulis berpura-pura
menunggu penerbangan malam. Padahal ya biasa saja, tak perlu pura-pura. Di
ruang tunggu banyak sekali orang tidur atau mengobrol sampai pagi. Petugas
keamanan bandara tampaknya tak punya persoalan dengan mereka yang tidur atau tidur-tiduran
di ruang tunggu. Kendati ada larangan tidur, bahkan sekadar duduk, di dekat
kaca lantai dua, banyak saya lihat orang tidur bersandar di kaca lantai dua dengan
aneka bawaan mereka.
Ketika duduk-duduk sambil menunggu baterai hp penuh,
seorang petugas keamanan datang dan duduk di sebelah saya tanpa bertanya
apa-apa, mencolokkan charger ke steker
lalu bermain-main dengan hp satunya. Biasa saja.
Dan saya teringat soal petunjuk arah ke warnet dari KL Sentral, tiket kereta api Malasyia ke
Hat Yai yang susah didapat tanpa booking online, rumah makan Haji Musa di
Siem Reap yang katanya dekat dari
Pub Street (ya dekat, kalau naik tuk-tuk, ke Angkor Wat juga dekat kalau tidak
jalan kaki), soal tidak adanya bus malam dari Siem Reap ke Phnom Penh, sangarnya petugas imigrasi perbatasan darat, terutama
perbatasan Kamboja - Vietnam, perilaku pengendara motor Saigon yang mengerikan
(menurut saya, mereka sangat terampil, lebih susah menyeberang di Pasar Minggu
daripada di Saigon), tarif taksi dari Pham
Ngu Lao ke bandara yang katanya 200.000 dong (pada kenyataannya cuma 160.000
dong, 180.000 dong kalau pesan lewat resepsionis hotel). Ada juga pemilik blog yang
memberikan jawaban menjengkelkan ketika salah seorang bertanya, katanya, “Ada
di buku saya halaman sekian.” Belum lagi blog-blog dalam bahasa Indonesia yang
selalu menyebut monk seolah-olah
dalam kosakata kita kata rahib sudah dihapus. Inilah paradoks abad kita,
informasi mudah didapat secara berlimpah, memilahnya setengah mati. Banyak
keluhan lain yang harus saya simpan karena mesti mencari air wudlu untuk salat.
Bukan perkara gampang berwudlu di bandara Saigon ini.
Kran wastafel disetel otomatis mengalir hanya dalam hitungan detik. Di kamar
kecil pun cuma ada tisu. Untunglah hari habis hujan, saya turun ke lantai dasar
mencari dedaunan yang basah. Salat di tempat seadanya, di dekat pintu darurat.
Matahari pun meninggi. Karena saya bukan pengelana
sejati, maka saya naik pesawat saja. Hahahaha. Biaya sih alasan sesungguhnya,
perjalanan darat dari Kota Ho Chi Minh ke Singapura lebih mahal daripada naik
pesawat.
 |
| Matahari menyembul di balik gedung-gedung di dekat Bandara Tan Son Nhat |
Karena tidak ada yang bisa diceritakan dari penerbangan
dengan ketinggian 35.000 kaki, saya tidur saja.
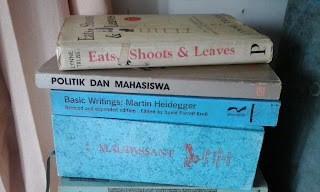

No comments:
Post a Comment